Singaraja |Nusantara Jaya News – Sejak dibuka pada 25 Juli 2025 di Sasana Budaya, Singaraja, Bali, oleh Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI Ahmad Mahendra bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, ditemani pendiri Singaraja Literary Festival (SLF), Kadek Sonia Piscayanti dan Made Adnyana Ole, SLF berlangsung , sublim, intim, dan penuh kesadaran.
Ini terlihat dari kawasan Gedong Kirtya dan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Ganesha tempat terselenggaranya SLF selalu dihadiri pengunjung yang saling mengenal dan saling mendukung.
Selama tiga hari (dari 25-27 Juli 2025), tempat-tempat lokakarya, pameran seni, dan diskusi berlangsung penuh kesadaran dan makna. Pengunjung datang dan pergi mengalir dalam kehangatan seperti telah memilih takdir masing-masing.
Singaraja Literary Festival adalah festival sastra yang berbasis alih wahana dari kekayaan sastra lontar yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh Yayasan Mahima Indonesia pada 2023 silam. Meski baru tiga tahun, SLF menjadi momen penting dalam lanskap kesusastraan regional, nasional, bahkan internasional, karena festival ini dapat menjembatani pengetahuan lama, kini, dan masa depan, dengan praktik-praktik kesenian kontemporer, seperti musikalisasi puisi, teater, film, dan buku karya sastra.
Tahun ini, SLF mengusung tema “Buda Kecapi” yang bermakna energi penyembuhan semesta. Tema ini menjadi kontekstual karena sastra memiliki kekuatan penyembuhan yang mendalam. Festival ini hendak membunyikan kembali harmoni antara sastra, kemanusiaan, dan penyembuhan—bukan hanya untuk pribadi, tapi juga bangsa dan alam semesta.
“Tema Buda Kecapi kami pilih karena relevansinya dengan kondisi sosial kita hari ini. Ada luka, ada krisis identitas, ada kehilangan akar. Dan sastra, khususnya yang bersumber dari warisan lokal seperti lontar, bisa menjadi penawar,” ujar Kadek Sonia Piscayanti, Direktur sekaligus Founder SLF.
Sonia menjelaskan, Buda Kecapi adalah salah satu naskah kuno yang tersimpan di Gedong Kirtya. Dalam teks itu, tersimpan gagasan tentang kehidupan yang seimbang, relasi harmonis antara manusia dan semesta, serta nilai-nilai penyembuhan melalui seni dan kebijaksanaan lokal. Inilah yang menjadi pijakan utama SLF 2025 untuk menggali naskah, menafsir ulang, dan mengalih wahanakannya dalam bentuk karya baru.
“Kami merancang festival ini sebagai proses pendokumentasian gagasan lintas masa, lalu, kini dan nanti melalui alih wahana dari teks lontar menjadi seni pertunjukan, karya sastra, bahkan film. Jadi kami tidak sekadar mengarsipkan masa lalu, tapi menghidupkannya dalam bentuk yang relevan dan bisa diterima generasi hari ini,” tambah Sonia.
Maka wajar jika Ahmad Mahendra, Dirjen P3K Kementerian Kebudayaan, mengatakan bahwa SLF menjadi satu-satunya festival sastra yang berbeda, khas, di Indonesia. Menurutnya, festival ini terlihat sangat organik, kolektif, gotong-royong dari berbagai pihak sangat terasa. Ia bahkan perlu mengatakan sangat terkesan dengan hal tersebut.
Cara membaca pikiran—atau ber festival—dengan topangan kesadaran kolektif ini tentu saja mengandung heroisme tertentu. Ia hendak memberi suara kepada yang selama ini tidak bisa bersuara. Dalam konteks festival ini adalah “menyediakan ruang bagi lebih banyak pikiran kaum intelektual yang terabaikan selama ini.” Sebab, kata Zen Hae dalam bukunya Sembilan Lima Empat (2021), sudah sejak lama kita ditantang oleh Gayatri Chakravorty Spivak lewat sebuah interogasi—yang juga menjadi judul esai panjangnya—“Can the Subaltern Speak?”
“Indonesia sangat berterima kasih kepada Singaraja Literary Festival karena telah merawat dan menghidupkan pengetahuan lontar yang tersimpan di Gedong Kirtya ke dalam banyak alih wahana kesenian kontemporer,” ujar Mahendra, bersungguh-sungguh, sebelum resmi membuka festival dengan memukul undir, alat musik tradisional Bali yang digunakan untuk mengiringi Tari Joged Bumbung.
Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatma menyambut baik atas terselenggaranya SLF tahun ini. “Ini menandakan kebangkitan sastra di Singaraja. Bahwa dulu Singaraja punya sastrawan yang terkenal bukan hanya di nasional tapi juga internasional, Anak Agung Panji Tisna, namanya,” terang Supit.
Selama tiga hari, lebih dari 60 program—mulai dari pertunjukan, diskusi, lomba, lokakarya, pemutaran film, pameran, sampai napak tilas—yang diisi dan diikuti para penulis, peneliti, budayawan, akademisi, seniman, dan publik dari berbagai penjuru dunia. Menurut Sonia, tahun ini panitia melibatkan ratusan penampil dan pembicara dari latar belakang yang sangat beragam. “Kami mengundang penulis dari seluruh Indonesia, penulis, akademisi dan penerjemah dari Kawasan Asia Pasifik, dan beberapa dari benua Eropa,” jelasnya.
Benar. SLF 2025 bukan sekadar panggung penampilan sastrawan, seniman, atau budayawan lokal Bali. SLF juga menjadi ruang bertemunya para tokoh besar dunia sastra dan budaya nasional dan internasional. Beberapa nama penulis dan sastrawan kenamaan yang hadir dan meramaikan festival ini antara lain Ratih Kumala, Dee Lestari, Henry Manampiring, Oka Rusmini, Andre Syahreza, Esha Tegar Putra, Putu Fajar Arcana, Wicaksono Adi, Ayu Laksmi, Herry Sutresna, Arif B. Prasetyo, Royyan Julian, Willy Fahmi Agiska, Kiki Sulistyo, AS Rosyid, dan sebagainya.
Sedangkan dari mancanegara, SLF menghadirkan sejumlah pembicara penting seperti Sanne Breimer (Belanda), Inderjeet Mani (India), Sudeep Sen (India), Lucy Marinelli (Italia-Australia), dan penulis-penerjemah lainnya.
SLF 2025 dibuka dan ditutup dengan seni pertunjukan (teater) yang digali dari lontar Buda Kecapi. Ini seolah menandai bahwa festival ini bukan sekadar perayaan atau atraksi kebudayaan. Lebih dari itu, SLF merupakan katalisator penyampaian identitas kebudayaan, tempat perayaan memori kolektif, pengembangan talenta dan ekspresi kreatif, tempat lahirnya pegiat budaya, dan tempat berkolaborasi serta berinovasi.
Festival ini juga menjadi jembatan penghubung antara pengetahuan masa lalu dan masa kini. Pula wadah yang mempertemukan sastrawan, penulis, akademisi, seniman, budayawan, peneliti, pelajar, dan masyarakat pada umumnya. Lihatlah, pada malam pembukaan, mereka semua duduk bersama tanpa ada jurang pemisah. Mereka semua ikut merayakan lontar, sastra, dan kebudayaan pada umumnya.
Di sinilah SLF menjadi sarana perekatan kohesi sosial, penggalian potensi-potensi budaya, sekaligus aktualisasi pengetahuan-pengetahuan dalam manuskrip-manuskrip (lontar) di Gedong Kirtya. Lontar mengajak manusia melihat masa kini dan masa yang akan datang dari perspektif masa lalu. Jiwa zaman yang ada dalam daun lontar menitikberatkan manusia kini untuk melihat, mendengar, dan merasakan lebih dalam—bahwasanya pengetahuan seperti air, mengalir dan menyejukkan.
Inisiator dan konseptor SLF—dalam hal ini Kadek Sonia Piscayanti dan Made Adnyana Ole—boleh dikata sedang memindai cabang-cabang budaya masa depan dengan mindful dan meaningful, penuh kesadaran dan makna, mengeksplorasi pertumbuhan pohon hayat kebudayaan masa lalu dan era sekarang.
Mindful dan meaningful, kata Sonia, berkesadaran dan bermakna, adalah ciri khas festival ini. Ia terhubung dengan ciri mindfulness, yaitu menampilkan kebaruan, fleksibel, mengakar konteks, dan menciptakan kategori baru selaras dengan makna. Sonia yang merupakan akademisi mengatakan bahwa salah satu kebaruan festival ini adalah melahirkan gagasan riset-riset berbasis lontar dan alih wahana ke berbagai bentuk kesenian baru.
Dalam Singaraja Literary Festival kearifan masa lalu dan praktik kebudayaan masa kini tampil dan dirayakan bersama-sama. Selain menyelam ke dalam memaknai kearifan lokal, SLF juga membuka diri ke luar, sebagaimana sifat budaya modern yang mengglobal.
Dalam konteks produksi pengetahuan baru, SLF juga merangsang pertumbuhan produksi pengetahuan baru di bidang sastra, seni pertunjukan, penerjemahan, alih wahana, hingga riset akademik. Bahkan metode yang dipilih juga narrative inquiry, pengalaman bertutur yang dekat dan akrab, bahkan untuk deskripsi hasil kajian akademik.
SLF juga dimaksudkan sebagai proses dokumentasi. “Kami bukan hanya ingin membuat peristiwa festival yang sekadar ada. Tapi ini menjadi proses dokumentasi, pemaknaan ulang, dan penciptaan gagasan baru. Karena itu, banyak program kami yang juga bersifat riset dan interpretasi,” ungkap Sonia.
Menurutnya, festival ini juga merupakan bentuk perlawanan terhadap pelupaan, terhadap sentralisasi pengetahuan, terhadap komersialisasi warisan budaya. SLF menjadi semacam panggung untuk suara-suara yang selama ini tidak terdengar atau sengaja dilupakan.
“Generasi muda harus tahu bahwa lontar bukan sekadar warisan, tapi cermin. Dan lewat cermin itu, kita bisa mengetahui tentang diri sendiri hari ini,” ujar Made Adnyana Ole, menginisiasi SLF yang juga dikenal sebagai penyair dan jurnalis senior.
Tahun ini juga Singaraja Literary Festival berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan RI untuk program MTN (Manajemen Talenta Nasional) Seni Budaya. MTN Seni Budaya yang berfokus di bidang sastra terdiri dari MTN Ikon Inspirasi dan MTN Asah Bakat. MTN Ikon Inspirasi berupa kegiatan seminar sastra bersifat publik sedangkan MTN Asah Bakat berupa workshop yang lebih khusus pada penulis pemula yang berbakat. Pada SLF 2025, telah diadakan MTN Asah Bakat penulisan novel oleh Dee Lestari tanggal 26 Juli lalu.
Bersama program Singaraja Literary Festival, MTN Seni Budaya hadir sebagai wadah pembelajaran, penguatan kapasitas, serta pemantik kolaborasi lintas generasi bagi para pelaku dan peminat sastra. (Tik/rls)


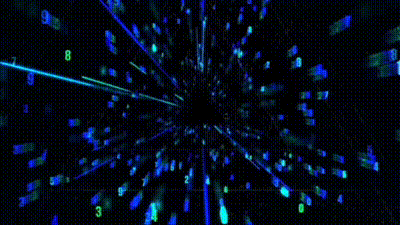 ****************************************
****************************************


















