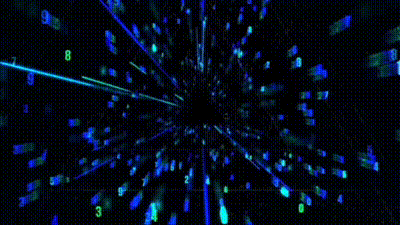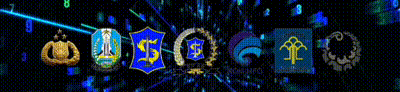Surabaya |Nusantara Jaya News – Mengawali tahun ini, Forum Pegiat Kesenian Surabaya (FPKS) kembali menggelar kegiatannya. Untuk kali ini adalah sebuah diskusi publik yang bertajuk Jagongan ala FPKS. Ini merupakan program FPKS sejak didirikan Mei tahun lalu.
Acara akan berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, pukul 19.00, di Galeri Dewan Kesenian Surabaya. Tema yang diangkat adalah Masa Depan Kesenian di Kota Surabaya. Di awal tahun ini menjadi momen penting membaca ulang kesenian di Kota Surabaya untuk kemudian melihatnya di masa depan.
Narasumber yang diundang dari berbagai kalangan, seperti kampus, seniman, pengamat, seperti DR Edi Dwi Rianto (Dosen Kajian Budaya Lokal FIB Unair), DR Agung “Tato” Suryanto (Kajur Seni Rupa STKW), DR. Wyna Herdiana (Wadek Fakultas Industri Kreatif Ubaya), Heri Lentho (Seniman dari Sanggar Jati Swara), Adnan Guntur (Penyair dari Saung Indonesia mewakili Gen Z), AH. Thony (mantan Wakil ketua DPRD Kota Surabaya dan kini jadi pengamat kebudayaan), Isa Anshori (Sekretaris TIM Transformasi Lembaga Seni Budaya Kota Surabaya), dan Henri Nurcahyo (budayawan) selaku moderator. Acara ini diselingi dengan pertunjukan Macapatan oleh Sinden rara Safira bersama Dosen Luar Biasa STKW, Darmono Saputro.
Menurut kordinator FPKS, Jil Kalaran, Surabaya bukan kota yang lahir dari kesunyian. Ia dibangun oleh suara teriakan pelabuhan, dentang-denting di bengkel-bengkel, doa-doa kampung dan bahkan nyanyian perlawanan. Kesenian Surabaya di masa lalu tumbuh dari denyut hidup rakyatnya. Bukan dari ruang-ruang berpendingin, melainkan dari gang sempit, balai RW, pelataran kampung hingga halaman pabrik.
Ludruk, parikan, ketoprak, musik patrol, dan seni tutur lainnya, misalnya, hadir sebagai cermin sekaligus senjata. Menghibur, mengkritik dan menjaga kewarasan kolektif. Dalam konteks ini, seni tidak dipisahkan dari hidup. Ia adalah bagian dari cara warga Surabaya bertahan, melawan sekaligus merayakan. Waktu terus berlari. Kota membesar, gedung-gedung menjulang dan kesenian pun pelan-pelan terdorong ke pinggir.
Di masa kini, posisi kesenian di Surabaya sering kali ambigu. Diakui secara simbolik, tetapi kurang dirawat secara substansial. Pemerintah hadir dalam bentuk festival tahunan, seremoni kebudayaan atau lomba-lomba yang rapi secara administrasi, namun sering kering secara gagasan. Seni diperlakukan sebagai “agenda”, bukan sebagai ekosistem. Seniman menjadi pengisi acara, bukan subjek yang diajak berpikir bersama.
Pendekatan birokratis membuat kesenian diukur lewat proposal, laporan dan angka kehadiran, bukan lewat dampaknya bagi kesadaran sosial. Ruang-ruang kesenian tumbuh lebih banyak karena inisiatif warga dan komunitas, bukan karena perencanaan kebudayaan yang matang. Banyak seniman Surabaya hari ini hidup di antara idealisme dan kelelahan. Berkarya dengan daya sendiri, sambil bernegosiasi dengan sistem yang belum sepenuhnya memahami kerja artistik sebagai kerja pengetahuan dan kerja kebudayaan.
Padahal, kota sebesar Surabaya semestinya tidak hanya sibuk mengurus infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur kultural. Jalan bisa mulus, gedung bisa megah, tetapi tanpa kesenian yang hidup, kota kehilangan daya refleksinya.
Kesenian adalah ruang bertanya, ruang menggugat dan ruang merawat ingatan. Tanpa itu, kota akan cepat lupa dari mana ia berasal dan ke mana seharusnya melangkah.
Untuk menuju masa depan, yang perlu dilakukan adalah bukan sekadar menambah anggaran atau event, melainkan mengubah cara pandang. Pemerintah perlu berhenti melihat kesenian sebagai ornamen, dan mulai memperlakukannya sebagai kebutuhan publik. Ini berarti, membuka ruang dialog yang setara dengan seniman, memberi kepercayaan pada komunitas, menyediakan ruang berkarya yang berkelanjutan, serta melindungi kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi yang kritis dan tidak nyaman.
Pendidikan seni juga harus diperkuat, bukan hanya sebagai pelajaran teknis, tetapi sebagai cara berpikir. Kota perlu mendukung arsip, riset dan dokumentasi kebudayaan agar generasi mendatang tidak hanya mewarisi cerita lisan yang terputus.
Kesenian Surabaya masa depan tidak cuma musti berakar pada tradisi, tetapi berani berinovasi. Bersandar pada lokalitas, namun terbuka pada perjumpaan global.
Jika Surabaya ingin memiliki masa depan kebudayaan yang sehat, maka ia harus berani merawat keseniannya hari ini. Bukan dengan memolesnya agar tampak aman, tetapi dengan membiarkannya hidup, berisik dan jujur. Sebab dari kota yang memberi ruang pada keseniannya, akan lahir warga yang berpikir, berempati dan tidak mudah tunduk pada lupa.
Dan mungkin, di situlah masa depan Surabaya benar-benar dimulai, pungkas Jil. (Red)