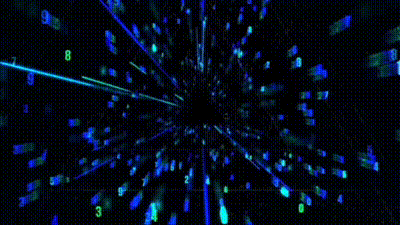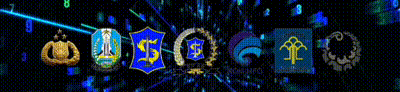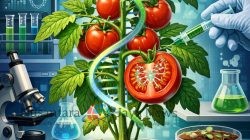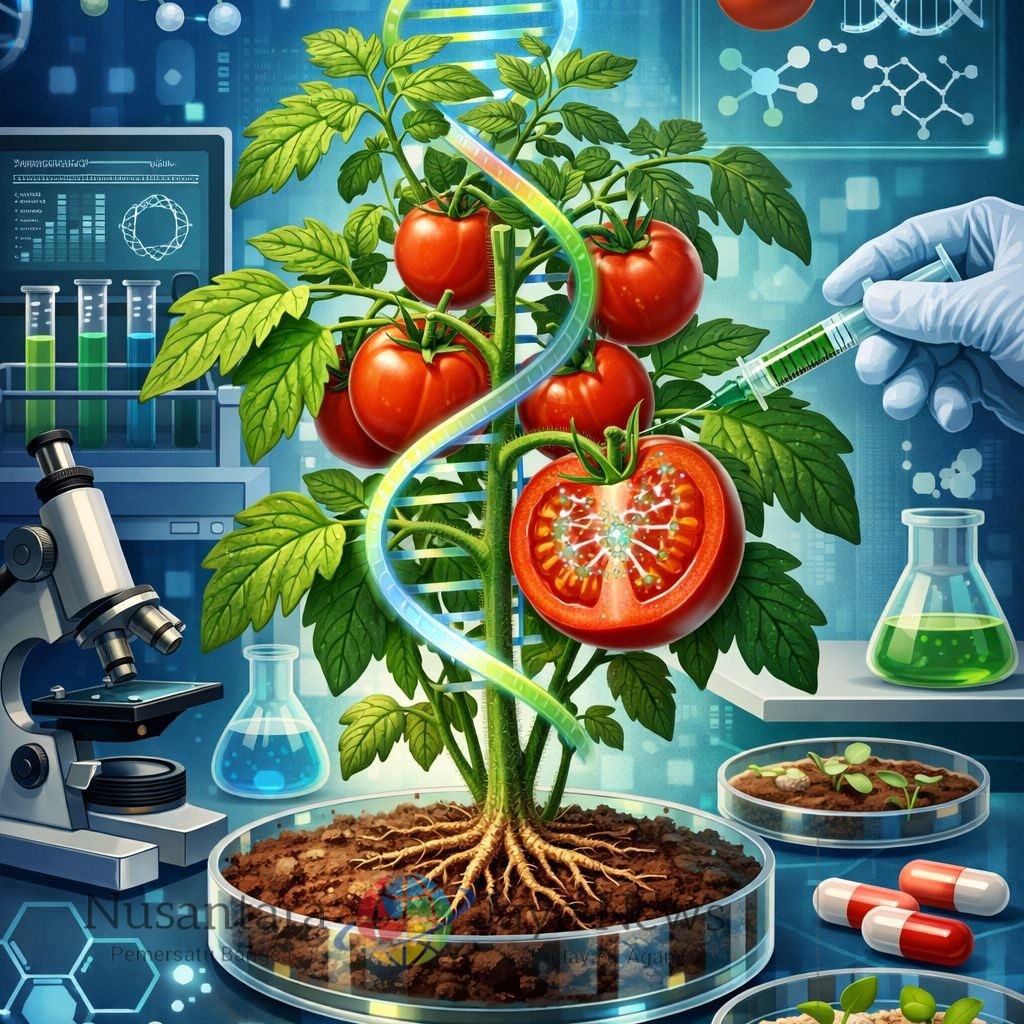Oleh : Basa Alim Tualeka (obasa).
Pendahuluan
Dalam pandangan umum, presiden, raja, kaisar, atau perdana menteri adalah pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Namun, realitas politik modern menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya bebas menentukan arah kebijakan. Kekuasaan sering kali terikat oleh sistem yang berlaku dan bahkan dikendalikan oleh kepentingan kelompok tertentu. Dengan kata lain, figur pemimpin bisa menjadi aktor utama, tetapi juga bisa sekadar simbol dalam panggung politik yang lebih besar.
1. Kekuasaan yang Terikat Sistem
Dalam negara demokrasi, seorang presiden maupun perdana menteri dibatasi oleh konstitusi, parlemen, dan lembaga yudikatif. Tujuannya adalah mencegah kekuasaan absolut. Raja dan kaisar dalam monarki konstitusional pun sebagian besar hanya berfungsi simbolis.
Contoh:
Presiden Amerika Serikat disebut sebagai orang paling berkuasa, tetapi ia tetap terikat oleh sistem checks and balances. Presiden Barack Obama misalnya, sering menghadapi kebuntuan dengan Kongres terkait program Obamacare.
Ratu Elizabeth II tidak memiliki kekuasaan nyata dalam pemerintahan Inggris. Peran politik praktis dijalankan sepenuhnya oleh Perdana Menteri dan Parlemen.
Pandangan Pakar:
Menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya Political Order in Changing Societies (1968), sistem politik modern justru menekankan pentingnya institusi ketimbang figur. Stabilitas pemerintahan tidak ditentukan oleh siapa yang berkuasa, melainkan seberapa kuat institusi yang mengendalikan jalannya pemerintahan.
2. Kepentingan Sebagai Faktor Pengendali
Selain sistem formal, seorang pemimpin juga harus berhadapan dengan tekanan kepentingan dari partai politik, kelompok bisnis, militer, media, maupun kekuatan internasional.
Contoh:
Presiden Soekarno pada akhir kekuasaannya terjepit antara kepentingan PKI, TNI AD, dan pengaruh blok internasional (AS dan Uni Soviet).
Perdana Menteri Jepang kerap jatuh bukan karena pemilu, tetapi karena tekanan faksi internal partai LDP.
Beberapa negara Afrika bergantung pada pinjaman IMF/Bank Dunia. Presiden di negara-negara ini sering tidak punya banyak pilihan selain mengikuti arahan lembaga internasional demi keberlangsungan ekonomi.
Pandangan Pakar:
Menurut Noam Chomsky, seorang intelektual kritis Amerika, banyak pemimpin dunia sesungguhnya hanyalah “wajah” dari kekuatan korporasi global dan elite ekonomi. Ia menyebut politik modern sebagai “manufacturing consent”, di mana kebijakan publik sering diarahkan oleh kepentingan segelintir orang kaya.
Francis Fukuyama menekankan bahwa dalam dunia modern, rule of law (supremasi hukum) seharusnya menjadi penyeimbang terhadap dominasi kelompok kepentingan, tetapi praktik di lapangan sering kali tidak demikian.
3. Simbol atau Penggerak?
Beberapa pemimpin berhasil membebaskan diri dari belenggu kepentingan dan menjadi agen perubahan. Nelson Mandela di Afrika Selatan, misalnya, mampu mengubah sistem apartheid menjadi negara demokratis yang lebih inklusif.
Namun, banyak juga pemimpin yang hanya menjadi simbol tanpa kendali nyata. Di Amerika Latin pada abad ke-20, sejumlah presiden hanya berfungsi sebagai boneka militer atau oligarki, tanpa kuasa membuat kebijakan independen.
Analisis Pakar:
Max Weber, sosiolog Jerman, menyebut tiga tipe otoritas: tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Dalam politik modern, otoritas legal-rasional (sistem dan hukum) lebih dominan dibanding kharisma seorang pemimpin. Akibatnya, meskipun seorang presiden atau raja memiliki karisma, ia tetap dibatasi oleh aturan sistem yang berlaku.
4. Pentingnya Kesadaran Rakyat
Kekuatan sistem dan kepentingan menunjukkan bahwa rakyat tidak boleh menyerahkan seluruh kepercayaan pada figur pemimpin semata. Partisipasi masyarakat, kebebasan pers, lembaga pengawas independen, dan keterlibatan sipil sangat penting agar pemimpin tidak sekadar menjadi boneka.
Pandangan Pakar:
Menurut Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, demokrasi yang sehat hanya bisa berjalan jika rakyat aktif mengawasi pemerintah. Tanpa partisipasi publik, sistem politik akan mudah disandera oleh kepentingan elite.
Miriam Budiardjo, pakar politik Indonesia, menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, melainkan juga mekanisme pengawasan yang berkelanjutan agar pemimpin tidak tergelincir dalam otoritarianisme ataupun menjadi alat kepentingan tertentu.
Kesimpulan
Presiden, raja, kaisar, maupun perdana menteri bukanlah aktor tunggal dalam panggung politik. Mereka selalu bergerak dalam batasan sistem dan kepentingan. Ada pemimpin yang berhasil menembus sekat ini dan menjadi agen perubahan, tetapi lebih banyak yang akhirnya sekadar simbol atau perwakilan dari kepentingan tertentu.
Oleh karena itu, rakyat perlu sadar bahwa demokrasi dan keadilan tidak bisa disandarkan hanya pada figur, melainkan harus diperjuangkan bersama melalui penguatan sistem, partisipasi publik, dan kontrol masyarakat.